Surat Di Gerbang Senja
"Mungkin hanya satu kata bila aku sedang berada di tepian ini. Kenangan. Tak pantas rasanya membenci semua yang pernah terjadi. Daun-daun yang mengering itu kita. Kita yang sudah menjadi sampah, menyatu dengan tanah."
Angin dingin yang pernah kita rasakan bersama, kini sudah kita rasakan masing-masing setiap malam. Aku selalu duduk disini menulis puisi. Dan hanya kepada bintang yang kulihat paling bersinar aku meratap dalam senyap.
Maaf bila ada rasa benci yang terpatri dalam hatiku. Sebuah rasa ketidak pedulian yang bukan berarti aku tidak memiliki rasa peduli. Bukankah lawan dari cinta adalah ke-tak-pedulian dan benci? Tapi bisa saja keduanya menjadi alasan. Ketika pertemuan pertama yang menjadi awal semua kegalauan setiap malam. Lihatlah keterpurukan pada masing-masing diri kita dalam mengais-ngais hidup hingga menangis.
Kita selalu memutar lagu yang sama setiap malam, bahkan suaramu sama persis ketika menyanyikannya. Apakah sekarang kau memilih untuk mematikan lagu-lagu tersebut bila tak sengaja kau mendengar dari sebuah radio atau televisi? Atau dari sebuah angkutan kota yang kau tumpangi memutar lagu tersebut, dan file lagunya sudah kau hapus permanen dari handphone maupun laptopmu. Jika iya, berarti kita sama. Dan apa peduliku pedulimu.
Mengapa senja selalu kita bicarakan dari waktu ke waktu? Bumi kita memang sudah senja, alam yang indah ini juga sudah senja, umurku dan umurmu semakin lama juga semakin senja, wajah negeri kita senja yang tak merah jambu lagi, dan kau lebih memilih senja yang tak bisa kita nikmati lagi bersama di negeri kita yang memang telah senja.
Apakah sekarang senja di negerimu seindah tempat ini? Biar aku tebak saja. Pasti indah dan warna langitnya berbeda. Burung-burung yang berterbangan dibawah atap langit senjanya juga pasti berbeda. Bagaimana dengan cuacanya? Pasti kalau sedang musim salju, pakaianmu setebal kasur Arimbi keponakannmu itu. Oh iya, kamu pasti menonton sepak bola club papan atas disana sambil berfoto dengan berbagai macam pose di depan stadion club sepak bola tersebut. Mungkinkah logat bicaramu juga sudah berbeda sekarang? Ada intonasi sengau dan tertahan bila mengucapkan selamat pagi atau selamat malam?
Kita masih muda. Katamu. Saat seperti inilah harus dimanfaatkan untuk menggapai cita-cita. Kita memang saling jatuh cinta, tapi apakah itu akan menghambat cita-cita? Latar belakang ekonomi kita disini setelah bencana juga menjadi alasan kuat untuk kau pergi. Setelah tak ada yang tersisa dari anggota keluargamu akibat bencana angin puyuh yang hampir meratakan kota kita, mengakibatkan ekonomi lumpuh, serta saat kita sama-sama menjadi relawan mengumpulkan dana dan menyuplai pakaian-pakaian bekas dari bantuan luar daerah, aku rasa saat itulah kita saling jatuh cinta. Setiap hangat mentari pagi di barak pengungsian kita lewati bersama sambil sarapan.
Mungkin kebersamaan dalam waktu dua tahun tak cukup untuk kita menjalin suatu hubungan yang resmi dan dihalalkan. Bukankah hidup itu pilihan? Ini yang kelak kupahami sebagai takdir setelah lelah berfikir tentangmu yang mendapatkan orang tua asuh di belanda dan melanjutkan kuliah di negeri kincir angin itu. Meninggalkanku.
Kita memang masih muda saat duduk bersama di bangku tepian menghadap ke danau malam terakhir sebelum kau pergi. Tapi umur setiap manusia siapa yang tahu. Kelahiran dan kematian semua telah teratur dan aku baru mengetahui bahwa setelah dua minggu kepergianmu, ada yang kau tinggalkan di rahimku. Aku mengandung anakmu. Anak kita.
Malam-malam hanya kulalui dengan menangis meratapi kebodohan muda kita. Aku menunggu kontak darimu setiap detik, hal yang paling beralasan mengapa hingga saat ini aku membencimu adalah ketika kukatakan ada janin diperutku dan kau hanya diam, sepi di seberang sana, padahal aku yakin kau mendengar tangisku dari telepon pertama dan terakhirmu itu.
Mengetahui hal yang sangat tak diinginkan terjadi pada anak perempuannya. Ayah murka, andai saja kau ada bersamaku saat itu, mungkin aku tak akan diusir dari rumah. Ibu memilih menikahkanku dengan salah satu kerabat jauhnya di pulau jawa, tapi ayah tetap dengan pendiriannya yang keras, apalah daya seorang ibu yang tak berkuasa di rumah. Ayah mengusirku dari rumah karena tak menginginkan bayi yang kukandung walau hitungannya adalah cucunya sendiri. Itu sangat memalukan, kata ayah. Sebagai tokoh masyarakat yang disegani di daerah tempat tinggalku, ayah bersikeras menyuruhku pergi dan bertahan dengan prinsip dan egonya. Lengkaplah derita serta kepedihanku. Aku melangkah keluar rumah diiringi tangis ibu yang hanya bisa pasrah.
Mungkinkah membenci waktu yang sudah lewat. Mungkinkah aku membenci janin yang kelak menjadi bayi lucu ini. Mungkinkah aku membenci keadaan yang menimpaku pada waktu itu. Aku harus bangkit dari keterpurukan. Tanpamu. Setelah keluar dari rumah, aku tinggal di sebuah kota yang sangat terpencil dan bekerja menjadi pelayan sebuah restoran makanan laut yang banyak di kunjungi tamu-tamu dari luar negeri. Tak ada yang mengetahui keberadaanku, bahkan Karina, teman dekatku, tak mengetahui dimana aku berada. Aku memilih menyendiri saja sambil menunggu bayi kita lahir. Ada satu waktu ketika rasa yang beraneka ragam menghantui benakku untuk mengakhiri hidup, siapa tahu kelak menjadi bintang yang abadi setelah mati, tapi pelan-pelan aku menyadari, inilah hidup yang sesungguhnya, tuhan mempunyai rencana untukku dan bukan aku yang menentukan hidup-mati atas nyawaku, selama masih bisa bertahan, aku akan tetap hidup walau tanpamu, dan saat itu aku yakin, bayi dalam kandunganku kelak akan menebus segala kesepianku bahkan dosa-dosa masa muda kita.
Anak kita lahir ketika senja. Seorang bayi perempuan cantik yang akhirnya kuberi nama Jingga. Seperti warna senja yang selalu kita pandangi di tepian danau ini. Di saat persalinanku, ibu datang untuk mengurusi semua keperluan dan menjagaku setiap malam. Sedangkan Ayah perlahan-lahan hatinya mulai luluh dan aku melihat rindu di mata Ayah yang begitu dalam kepadaku.
Jingga selalu menjadi alasan utamaku untuk tetap semangat menjalani hari-hari. Aku sangat menaruh harapan yang tinggi kepadanya. Aku berjanji akan selau memberikan cinta setiap hari. Saat Jingga mulai mengucap kata mama, hanya air mata yang tiba-tiba mengalir dan aku menangis tanpa isak. Bukankah menangis tanpa isakan merupakan rasa yang terdalam serta tak bisa di ungkapkan dengan kata-kata dalam bahasa apapun.
Sebagai seorang perempuan yang mempunyai seorang anak tanpa suami, itu juga merupakan beban yang sangat berat bagiku. Tapi aku sudah menutup mata, telinga bahkan hatiku. Aku mempunyai jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang terlontar. Jingga adalah yang paling utama untukku. Banyak lelaki yang mencoba mendekatiku dengan bermacam-macam janji dan alasan-alasan yang terkadang membuatku gamang. Aku hanya perlu beberapa waktu lagi untuk bisa benar-benar membuka hati.
Bagaimana senjamu hari ini disana? Apakah berwarna jingga? Di tepian ini sekarang aku melihat dua jingga sekaligus. Yang satu disampingku dan satunya lagi di langit. Tahu kah kau jingga yang di sampingku seperti apa? Biar sedikit ku ceritakan. Sekarang dia berumur empat tahun tiga bulan. Jingga cantik. Kata ibu dia sepertiku. Sejak masih bayi aku sudah memandikannya sendiri dengan tanganku. Dia rakus meminum air susu yang mengalir dari tubuhku. Ketika umurnya dua tahun, aku pernah lengah dan itu menyebabkan jingga terjatuh dari kereta dorong, tapi dia tidak menangis. Jingga memang anak yang lincah. Setiap pagi aku menari bersamanya menikmati embun yang segar dari daun. Ah, kau pasti sangat gemas bila melihatnya. Tapi apakah dia mengenalimu? Tidak. Aku tak pernah menceritakan apapun tentangmu. Maafkan aku. Bukannya aku tak ingin menceritakan padanya, tapi kelak, ketika aku mulai sanggup bercerita tanpa ada airmata bila menyebut namamu.
Dengan siapa kau melewati senjamu hari ini disana? Apakah dengan jinggamu juga. Peduli apa aku. Bukankah lawan dari cinta itu adalah tak peduli. Dengan atau tanpamu hidupku juga berjalan pada akhirnya, walau perlahan. Hanya satu hal yang ingin ku ketahui langsung darimu. Apa alasan kau tak menghubungiku dan menghilang?
Masih ada cahaya terang untuk Jingga kelak. Lagu yang dulu sering kita dengarkan bersama setiap malam memang menunjukan semangat yang tak boleh padam. Walau cahaya bintang mungkin memudar dan kita tetap tak bisa mengubah apa yang sudah pernah terjadi. Lalu, apakah rindu merupakan sebuah bagian dari benci? Inginnya aku tak peduli. Karena sepertinya saat ini aku sedang mendengar kau melantunkan lagu tersebut.
“...Cos all of the star are fading away just try not to worry you’ll see them someday, take what you need and be on your way and stop crying your heart out...”
Aku hanya terkenang-kenang dengan suaramu yang mirip sekali dengan penyanyi aslinya bila menyanyikan lagu itu. Apakah disana masih sering kau menyanyikannya? Aku rindu tapi benci. Aku akan tetap bersinar seperti bintang yang kau tunjuk di malam terakhir kita duduk di tepian ini. Apakah kau masih menjadi bulan sabitnya yang suatu saat nanti, bintang dan bulan sabit tersebut akan membentuk satu gugusan yang berformasi tersenyum di langit. Ini hanyalah surat di gerbang senja yang tak akan pernah sampai padamu. Mungkin hanya akan aku larungkan di atas air hingga hanyut atau kubuang di tepian dan menjadi sampah termakan tanah seperti kenangan kita.
***
Kijang 07-02-2011
Lirik lagu stop crying your heart out by oasis
Cerpen ini juga terdapat di buku Tepian (Kota ini belum mati)
Tertarik dengan Iklan di bawah ini? Silahkan klik Gambar untuk info lebih lanjut.




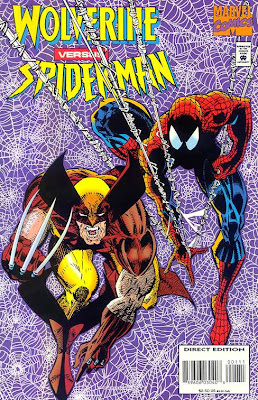
Comments