Akhiran Yang Sama
Musim panas telah berlalu. Begitu tak menyenangkan dengan hujan yang akan selalu datang. Apalagi kalau hujan itu datang waktu sore. Yang berarti aku akan kehilangan waktu ternikmatku untuk tenggelam dalam buku-buku yang ku baca di bangku taman. Sendiri, bersama angin dan angan-angan.
Aku berharap sore ini hujan tak mencampuri urusanku dengan buku-buku dan angin. Dari kaca jendela kantor mendung terlihat siap. Mungkin hujan akan akrab dengan tanah hingga menjelang malam. Tapi itu baru kemungkinan dan bukan harapanku.
Sepulang kerja. Dengan beberapa buku. Langkah kaki terayun pelan menuju tempat favoritku. Bangku taman kota yang menghadap ke jalanan. Mendung masih menggantung di ujung langit. Kubiarkan pasrah saja kalau-kalau hujan datang tiba-tiba. Aku telah larut bersama salah satu buku di sebuah bangku kayu kini.
Matahari sudah tak terlihat karena tertutup awan, mendung masih berkelabat, senja telah habis ketika kulangkahkan kaki meninggalkan bangku taman. Aku sudah berjalan cukup jauh saat merasa ada sesuatu yang janggal, seperti ada yang tertinggal. Salah satu bukuku. Mendadak panik. Aku berbalik dan berlari menuju bangku taman.
“Itu bukuku.” Sedikit aku berteriak.
Seorang laki-laki menoleh di bangku taman yang tadi kududuki. Ia sedang memangku laptop. Sepertinya sedang mengerjakan sesuatu atau mengetik.
“Ambil sendiri.” Dengan suara datar menjawab pertanyaanku, lebih tepatnya mungkin berimprovisasi saja atas teriakkanku yang sedikit keras tadi. Lalu kembali menatap ke layar laptopnya.
“Maaf, saya...” Aku bersuara. Ia berpaling dari layar. Menatapku. Dari matanya seperti mengisyaratkan sesuatu dengan tatapan seolah tak menyukai kehadiranku.
“Itu bukumu, ambilah dan jangan membaca di sini, duduk di tempat lain saja.” Suaranya masih datar. Aku mendadak terkejut. Sok Cool. Batinku. Tapi tampangnya lumayan menarik. Siapa juga yang mau membaca di hari yang beranjak gelap di sini.
Aku bergegas mengambil buku dan langsung ngeloyor pergi. langkahku tergesa, hari mulai gelap. Beberapa langkah setelah aku pergi. Tiba-tiba aku ingin menoleh ke arahnya. Sejenak melihat laki-laki tadi. Ia masih duduk di sana larut dengan kegiatannya. Mengapa aku merasa kesal. Sudahlah.
Aku sedang tenggelam dalam buku yang kubaca saat mendengar langkah kaki mendekat. Aku memalingkan wajah. Lelaki sok Cool kemarin sore itu sudah berada di sisiku dengan pandangan lurusnya. Aku melihat ke sekitar.
“Duduk di sana saja, di tempat lain, bangku ini milikku sampai nanti hari beranjak gelap.”
Aku juga bisa sok Cool dan baru saja melakukannya. Dengan sedikit memasang wajah yang datar dan berbicara menggunakan intonasi sedikit dipertinggi, seperti yang ia lakukan kemarin sore, lalu aku kembali tenggelam ke dalam buku yang kubaca. Dalam hati merasa menang. Impas. Satu sama. Dan ia pun melangkah pergi. Tetapi mengapa seperti ada penyesalan dalam hatiku. Apa karena dia lumayan menarik? Ah sudahlah.
Keesokan harinya di ujung senja yang mendung, ketika hendak melakukan ritual sore seperti biasa, membaca di bangku taman. Tempat duduk itu sudah terisi oleh lelaki yang larut dengan layar laptopnya. Ia menguasainya. Bangkuku itu, sudah berbulan-bulan tak ada yang menempatinya di waktu-waktu seperti ini, selalu aku, dan hanya aku yang pasti menduduki bangku itu sambil membaca di senja hari. Entah mengapa aku merasa sesuatu telah terenggut, telah diambil, dan aku merasa jengkel. Dengan tenang. Aku mendekat lalu duduk di sebelahnya. Berharap kedatanganku mengganggunya dan ia mengalah lalu pergi. Ia menoleh sejenak. Namun tak mengusirku, aku juga tak berani mengusirnya, seperti yang sudah-sudah. Mungkin merasa impas atau...
“Apa kita impas sekarang?.” Ia membuka percakapan. Aku mengangguk. Tersenyum tipis. Ia kembali ke layar komputer kecilnya itu. Tanpa ada pembicaraan selanjutnya, lalu aku mulai membaca, tapi pikiranku tak larut ke dalam buku. Bukan merasa tak nyaman, lelaki di sampingku saat ini cukup menarik. Hanya saja, biasanya dengan angin aku berteman ketika membaca, namun saat ini aku berbagi bangku dengan seseorang. Kali ini aku lebih cepat berada di bangku taman. Segera pulang beristirahat.
Hari selanjutnya di bangku taman kembali aku bertemankan lelaki cukup menarik itu. Aku membaca dan ia menatap layar laptopnya mengetik entah apa. Tak ada pembicaraan saat kami sama-sama mengisi bangku itu. Larut dalam kegiatan masing-masing. Ia tak berbicara dan aku segan untuk memulai.
Setiap senja di bangku itu kini kami saling berbagi tempat. Tak pernah ada orang lain selain kami. Sebelum lelaki itu hadir, aku yang pasti menguasai tempat itu. Berbulan-bulan lamanya aku duduk sendiri berteman angin. Bersandar pada senja. Hilang kembali untuk datang keesokan hari. sendiri. Tanpa berbagi. Tapi sekarang sudah hampir sebulan kami berbagi tempat di bangku taman. Masih tanpa pembicaraan.
Suatu hari aku datang lebih cepat. Pada hari minggu yang lengang dan tenang aku datang satu jam lebih cepat dari biasanya, ia belum berada di sana. Aku berencana melakukan sesuatu. Yaitu ketika ia datang, lalu aku akan langsung pergi meninggalkannya. Apa reaksinya?
Aku termenung membayangkan ia mengatakan sesuatu. Seperti mencegah agar tetap tinggal. Lalu berbicara-bicara, menanyakan hal-hal yang berupa basa-basi atau apa saja. Tiba-tiba lamunanku terhenti ketika mendengar langkah kaki mendekat. Aku bergeming. Itu pasti dia. Aku bersiap membereskan buku-buku dan memasukkannya ke dalam tas jinjingku lalu bergegas untuk pergi.
Langkahku berpapasan dengannya. Ia berhenti. Memandangku dengan datar. Lalu menyerahkan sebuah buku. Aku terkejut. Tapi tanganku menerimanya, mengambil buku yang ia sodorkan itu. Buku yang sangat tebal. Lalu ia terus melangkah ke bangku taman. Tanpa berbicara apapun. Alih-alih bertanya atau berkata sesuatu, malah dengan santai membiarkan aku terpaku di setengah perjalananku meninggalkan tempat itu.
Sesuatu yang telah kurencanakan sepertinya hendak kubatalkan saja. Aku hendak berbalik kembali duduk bersamanya seperti biasa, tetapi egoku telah meninggi dan aku tetap beranjak pergi. Dari kejauhan aku melihatnya tenggelam di layar komputer portablenya. Kini aku melangkah sendiri berteman angin.
Sudah dua hari aku tak mengunjungi tempat favoritku saat senja. Hujan datang berturut-turut selama dua sore. Sepertinya aku merasa kehilangan sesuatu bila tak mengunjungi tempat itu, sudah menjadi suatu kebiasaan yang teratur. Apalagi dengan kehadiran lelaki cukup menarik yang jarang melakukan pembicaraan itu. Aku berharap esok cerah. Ingin mengucapkan terimakasih padanya atas pemberian buku tempo hari.
Arus balik. Pramoedya Ananta Toer. Buku yang ia berikan. Salah satu buku yang sudah lama sekali ingin kubaca. Buku setebal 760 halaman yang menceritakan Epos kejayaan Nusantara diawal abad 16. Beberapa minggu terakhir ini aku hanya mengulang membaca buku yang telah habis kubaca. Aku belum punya buku bacaan baru, belum cukup uang untuk membeli beberapa list yang telah kubuat. Dengan buku pemberiannya ini, aku merasa senang. Setidaknya kali ini aku tak membaca ulang beberapa buku saat duduk di bangku senja hari nanti. Dan dengan ketebalannya itu, yang baru saja kubaca beberapa halaman, akan lebih dari cukup untuk kuhabisakan selama beberapa senja di sana.
Pertanyaan yang berkecamuk selama dua hari tak berada di sana adalah perihal lelaki itu. Kami tak saling mengetahui nama. Siapakah dia dan apa namanya? Mengapa aku memikirkannya? Sepertinya secara perlahan ia mulai mengisi hari-hariku.
Di suatu sore yang cerah. Selepas hujan semalam, lanskap sangat bersih, dedaunan terlihat lebih hijau, batang-batang pohon nampak kokoh dengan gurat-gurat yang terlihat, air hujan yang turun benar-benar membersihkan alam. Ketika aku sampai di bangku, ia sudah di sana, namun tanpa komputer kecilnyanya, ia hanya duduk, kakinya selonjor jatuh ke tanah dan disilangkan, kedua tangannya terlipat di bawah ketiak, pandangannya lurus ke rerumputan yang bergoyang.
“Hai...” Sapaku. Memberanikan diri memulai pembicaran. Ia menolehkan kepala ke arahku. Tetap diam. Senyumpun tak mengembang.
“Umm.. Terimakasih bukunya.” Lanjutku berucap. Lalu duduk di sebelahnya. Ia hanya mengangguk.
“Apa kabar?” Aku terkejut. Ia berbicara menanyakan kabar. Sudah dua hari kami tak bertemu dan sekarang ia bertanya tentang keadaanku. Aku tersenyum, mencoba memasang wajah seramah mungkin. Sebenarnya. Aku ingin memancingnya dengan senyuman supaya ia juga tersenyum. Pasti akan lebih menarik bila itu dilakukannya.
“Baik-baik saja. Dan kamu?.” Aku balas bertanya.
“Kalau sakit, saya akan kabari kamu.” Ia menjawab. Jawabannya itu membuatku tertawa.
Dan ia akhirnya tersenyum. Aku lebih tersenyum darinya. Dan itu indah.
Sekarang kami duduk di bangku taman sambil berbicara. Aku tak membaca. Buku yang ia berikan ku letakkan di atas tas jinjingku. Ia juga tak seperti biasanya tenggelam ke dalam layar komputernya.
“Apa yang membuatmu ingin selalu kembali ke tempat ini, emmm.. gadis yang suka membaca?”
Aku tersenyum. “Namaku Sandra.”
Dan itulah pembicaraan kami setelah hampir satu bulan berbagi bangku. Lelaki yang akhirnya kuketahui bernama Edward itu ternyata seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsi. Aku mengira selama ini ia mengerjakan tugasnya dengan laptopnya itu, tapi ternyata dugaanku salah. Ia sedang menulis sebuah novel.
“Wah jadi kamu sedang menulis novel?” Aku takjub. Selalu akan takjub dengan orang yang menulis sebuah cerita. Mereka pasti orang-orang yang memiliki imajinasi sangat tinggi. Ia hanya tersenyum, mengangkat alisnya.
Hari ini ia mengantarku pulang. Berjalan kaki berdua menyusuri pinggiran kota. Sangat menyenangkan, sambil saling bertukar pandang dan berbicara ringan.
“Mengapa menulis di tempat itu?” Sesuatu yang sudah lama ingin kutanyakan akhirnya lepas begitu saja dari mulutku. Ia tampak sedang berpikir sejenak untuk menjawab pertanyaanku.
“Aku mungkin tersesat..” Sambil menahan tawa ia menjawab. Aku merasa itu adalah jawaban konyol. Tapi sepertinya ia mengetahui gelagatku yang tak puas dengan jawaban itu.
“Hmmm... adakah jawaban yang lebih lain atau paling lain sekalipun?”
“Yah... mungkin saja begitu. Kafe tempat di mana saya biasa menghabiskan sore untuk menulis telah habis terbakar. Kamu pasti ingat kejadian itu?” Ia yang bertanya kali ini. Aku sejenak mengingat kejadian beberapa minggu lalu di sudut kota yang terjadi kebakaran. Aku mengangguk.
“Sejak saat itu saya kehilangan tempat favorit dan akhirnya sampai ke tempat favoritmu tersebut.” Mengapa sekarang ia jadi sering tersenyum? Sesuatu yang begitu langka karena hari-hari berlalu bersamanya ia selalu memasang wajah yang dingin, kaku, seperti robot.
“Mengapa tidak di tempat lain setelah mengetahui bahwa itu adalah tempatku, dan... kenapa jarang bicara?”
“Mungkin memang harus seperti itu.” Ia berkata pelan.
Sepanjang perjalanan ia mengantarku pulang kami saling bertukar cerita. Namun tiba-tiba kepalaku terasa berat. Sebenarnya ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Pusing di kepalaku mulai menyerang. Aku teringat bahwa belum meminum obatku sejak siang tadi. Langkahku mulai limbung dan secara reflek kurangkul lengan Edward untuk mencari keseimbangan.
“Kamu kenapa?” Cepat ia merangkulku. Wajahnya tampak panik.
“Tak mengapa, hanya sedikit lelah” Jawabku lirih hampir tak terdengar, bahkan oleh telingaku sendiri. Kini matanya yang bertanya dalam bingung.
“Hey wajahmu pucat... biar saya antar ke dokter..” Lalu hanya suara berdesing yang kudengar. Ia kini menopangku. Membimbing langkahku pelan-pelan lalu menghentikan taksi.
Di dalam taksi ia terlihat cemas, barangkali terkejut melihat kondisiku yang tiba-tiba menurun.
“Ada apa Sandra?” Pelan ia bertanya.
“Saya belum minum obat, sudah beberapa tahun ini saya harus rutin meminum obat empat kali sehari dan tidak boleh terlalu lelah. Saya mengidap penyakit ganas yang sudah cukup akut.” Aku menjelaskan. Ia tak nampak tersentak, hanya pandangannya kosong. Sepertinya hampa. Setelah itu aku tak ingat apa-apa.
Tiga bulan berlalu setelah kejadian itu. Di bangku taman aku kembali berteman buku, angin dan angan-angan. Aku tak pernah melihatnya lagi. Tak sadarkan diri di rumah sakit selama hampir satu bulan. Memang seperti ada yang hilang namun harus kuanggap biasa. Aku memang terbiasa dengan apapun yang menjadi kenangan. Namun aku bukan orang yang mudah putus asa. Semua yang datang pasti akan pergi. Tak butuh ucapan selamat datang maupun selamat tinggal. Kesendirian adalah hidupku. Menghitung waktu mundur untuk juga pergi meninggalkan segalanya tanpa harus mengucapkan selamat tinggal. Seperti ketika kedatanganku lahir di dunia ini. Tak ada yang mengucapkan selamat datang. Seingatku, aku besar hingga kini di panti asuhan.
Untuk hidupku “Mungkin memang sudah harus seperti itu.” Dengan akhiran yang selalu sama.
Sebuah paket berisi buku kuterima tadi siang di kantor. Dari Edward Gilang Pratama. Novel yang ditulisnya telah terbit. Ada sepucuk surat yang berisi ucapan kata maaf, sebenarnya selama dua minggu ia menunggu dan menemani hari-hari tak sadarku di rumah sakit, karena ada sesuatu hal, ia harus pergi meninggalkan kota dan belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Ia juga menyatakan bahwa ia baik-baik saja. Dan secepatnya akan kembali. Novel itu ia dedikasikan untukku. Ia juga menanyakan kabar dan keadaanku saat ini.
Lirih aku berucap. "Aku baik-baik saja. Semuanya sedang mengarah kesana."
Aku menatap hampa buku yang kupegang. Tanganku gemetar. Entah seperti apa Endingnya.
***
Kijang, Oktober 2011




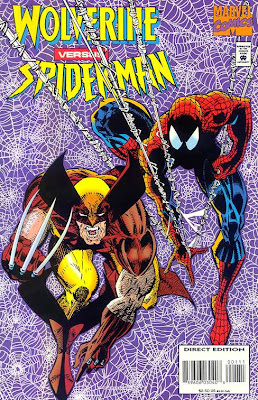
Comments