Jurnalisme Sastrawi
Jurnalisme. Sastra. Satu berada di ranah fakta. Satu lagi di ranah fiksi. Jurnalisme sastrawi, sebuah konsep yang kontrakdiktif: fiksi atau fakta?
Ia seratus persen jurnalisme. Hanya saja ditulis dengan gaya sastra. Ia juga seratus persen fakta, bukan fiksi.
Jurnalisme sastrawi merupakan sebuah metode penulisan dalam jurnalistik di samping metode penulisan yang sudah ada. Pada teknik penulisan dalam jurnalistik lama, umpamanya, dikenal beberapa jenis artikel seperti berita lurus dan karangan khas.
Berita lurus, sebagai contoh, terdiri atas beberapa elemen 5W 1H. Elemen yang dianggap terpenting menjadi teras. Elemen-elemen selanjutnya memberikan penjelasan tambahan atas teras. Informasi tambahan semakin lama semakin tidak penting atau semakin bisa dibuang. Struktur penulisan semacam ini memungkinkan editor menyesuaikan teks berita dengan keterbatasan ruang secara gampang. Jika ruang takmampu menampung teks berita secara penuh, bagian terbawah dipotong, atau dihapus lantaran kurang penting dibanding bagian di atasnya.
Nalar struktur penulisan semacam ini adalah bahwa ruang pada surat kabar, yaitu kertas, merupakan bagian beban produksi. Dengan begitu, sebuah penulisan berita harus hemat dan tepat guna, beradaptasi dengan ketersediaan halaman koran yang terbatas.
Di tanah air, seorang wartawan harus mengumpulkan berita jenis ini setidaknya tiga buah per hari kepada editor. Ia harus bisa mendapatkan peristiwa yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat.
Tuntutan target dan tenggat mendorong wartawan- terutama wartawan di ibukota- mengambil jalan pintas dengan membuat ‘talking news.’ Artinya, berita sekadar ditulis berdasarkan kutipan pendapat orang tentang sebuah peristiwa, bukan peristiwa itu sendiri. Biasanya sumbernya adalah para pejabat atau birokrat, atau tokoh-tokoh elit. Dengan begitu, sukar bagi wartawan untuk dapat menghasilkan berita yang berkualitas.
Bandingkan dengan kualitas penerbitan surat kabar regional.
“Saya kaget begitu tahu kalau The Nation hanya meminta saya menulis satu berita per pekan,” cerita Andreas Harsono tentang pengalamannya sebagai wartawan lepas di harian yang berkantor di Bangkok itu. Bayarannya juga tinggi: 3.000 dollar Amerika per artikel. Dengan begitu, wartawan dapat memfokuskan diri membuat artikel yang bermutu.
“Dengan menjadi wartawan lepas saja, orang bisa hidup layak,” katanya.
Andreas mengatakan, pendapatan The Nation kira-kira sebanding dengan Kompas. Tapi gaji awal wartawan Kompas jauh lebih kecil, di bawah 400 dollar. Bahkan gaji wartawan harian lain semisal Koran Tempo dan Media Indonesia, nilainya lebih kecil lagi, di bawah 250 dollar. Wartawan di Indonesia memang cenderung dianggap sebagai faktor produksi yang ketimbang mitra profesional perusahaan. Dalam kondisi seperti inilah wartawan akhirnya tergiur menerima ‘amplop.’
Eksistensi wartawan dalam penulisan berita dalam surat kabar di Indonesia menjadi nihil. Dalam penulisan berita, misalnya, sering kali karya wartawan tidak dihargai. Identitas wartawan digantikan menjadi kode-kode singkatan yang takbermakna di bagian ekor.
Di Kompas, hanya artkel tertentu yang dianggap bagus yang nama penulisnya dipampang secara by line. Padahal, semestinya setiap artikel memajang nama-nama reporter sebagai bentuk pertanggungjawaban terahadap publik. Dengan by line, seorang wartawan takkan berani menulis sebuah berita seenaknya, karena ia sadar publik bisa mempertanyakannya dengan kritis. Bahkan, kalau perlu menggugatnya. Dengan begitu, kualitas liputannya akan meningkat. Akan tetapi, boleh dibilang, media cetak di tanah air mengembangkan sebuah jurnalisme dengan gaya sendiri, yang berbeda dengan arus utama global.
Di sini jurnalisme sastrawi memberi tempat bagi wartawan untuk mengakutalisasikan keberadaan dirinya. Sebab, ia menuntut seorang wartawan untuk mampu membuat narasi, ataupun deksripsi yang rinci, hidup, kontekstual, dan relevan. Tidak mungkin seorang wartawan hasil seminggu pelatihan – hanya dengan bekal 5W 1H — bisa memenuhi standar karya jurnalisme sastrawi. Sayangnya, proses perekrutan wartawan oleh media massa cetak nasional mengesampingkan kemahiran menulis ini.
Perekrutan biasanya menerapkan syarat-syarat yang ketat seperti indeks prestasi minimum, usia maksimum, dan lulus serangkaian prosedur psikotest yang rumit dan panjang. Namun, ia menomorduakan kematangan dan kemampuan bahasa. Ini mengakibatkan reporter-reporter baru tidak mampu menghasilkan artikel yang kuat. Baik dalam aspek liputan maupun tulisan. Gunawan Muhammad sampai-sampai mengeluh karena dalam setiap angkatan baru Majalah Tempo yang berjumlah 20 orang, paling hanya satu atau dua orang yang mempunyai kemahiran menulis.
Tom Wolfe, seorang wartawan Amerika, memberikan batasan jurnalisme sastrawi pada tahun 1973 dalam antologi berjudul The New Journalism. Isinya kumpulan artikel-artikel terkemuka pada saat itu. Ia menyebut artikel-artikel itu sebagai ‘jurnalisme baru,’ sedangkan para penulisnya ‘jurnalis baru.’
Wolfe membuat empat karakteristik jurnalisme baru yang membedakannya dengan jurnalisme konvensional. Pertama, pemakaian konstruksi adegan per adegan. Kedua, pencatatan dialog secara utuh. Ketiga, pemakaian sudut pandang orang ketiga. Keempat, catatan yang rinci tentang gerak tubuh, kebiasaan, dan pelbagai simbol kehidupan orang-orang yang muncul dalam peristiwa.
Konstruksi adegan per adegan, sebagai contoh, menggantikan pemaparan kronologis, ataupun eksposisitoris yang lazim pada jurnalisme konvensional. Dengan teknik seperti ini, imajinasi pembaca akan menangkap sebuah gambaran peristiwa bak menonton sebuh film. Ini kombinasi kemampuan seorang wartawan sekaligus jurnalis, kata Wolfe.
Dalam adegan biasanya muncul sebuah dialog. Dialog bukan sekadar memperlihatkan percakapan, tapi juga menggambarkan sikap, dan pemikiran narasumber. Dengan begitu, wawancara bukanlah sekadar proses merekam pembicaraan sambil lalu. Ia dilakukan secara mendalam, berulang-ulang dengan pelbagai sumber untuk mendapatkan sebuah rekonstruksi pikiran dan emosi dengan tepat. Untuk itu, latar belakang narasumber perlu dipelajari. Dengan kata lain, tiap kata yang dikutip untuk dialog hendaknya bisa bermakna.
Adapun penggunaan sudut pandang ketiga bermaksud merepresentasikan pandangan mata narasumber. Dengan cara ini, pembaca seolah masuk kedalam peristiwa. Pembaca akan melihat apa yang dilihat narasumber, dan merasakan apa yang mereka rasakan.
Karakteristik terakhir adalah rincian tentang gerak, perilaku, kebiasaan, gaya, cara atau adat, pakaian, dekorasi rumah, wisata, makan, merawat rumah, bagaimana berhubungan dengan anak, dengan pembantu, teman sebaya, bawahan, pose, dan lambang-lambang lain. Semua itu menjelaskan karakter dan konteks narasumber dalam komunitas, bagaimana ia membina interaksi dengan orang lain, bagaimana kedudukannya di dalamnya, serta bagaimana ia mengungkapkan pikiran dan harapannya.
Jurnalisme sastrawi menjadi proyek uji coba Majalah Pantau semenjak akhir Desember 2000. Ini majalah pemantau media massa yang melulu bicara tentang media dan jurnalisme. Ia mendapatkan sokongan dari Ford Foundation 200.000 dollar Amerika. Pantau menerapkan sistem wartawan lepas, sedangkan artikel dihargai 400 rupiah per kata. Jumlah kata pada setiap artikel bisa melampaui 10.000 kata.
Boleh dibilang, Pantau adalah proyek idealisme yang mahal. Padahal anggarannya hanya mampu membiayai 40 peratus biaya produksi per edisi. Maka, taklama, Pantau bubar pada tahun 2003. Tidak ada penanam modal yang bersedia membiayai proyek mercusuar ini.
Dengan demikian, apakah jurnalisme sastrawi bisa diterapkan di tanah air? Kegagalan Pantau menunjukkan bahwa jurnalisme sastrawi tidak gampang dipraktikkan, jika bukan tidak mungkin. Biaya produksi membengkak karena ruang halaman harus tersedia lebih banyak.
Selain itu, ongkos penulisan per artikel sendiri mahal karena ia butuh riset yang sungguh-sungguh dan verifikasi berulang-ulang. Konsekuensinya, harga jual per eksemplar sukar dipatok rendah. Biaya pemasangan iklan pun menjadi amat mahal, sehingga pengiklan akan berpikir-pikir apakah berharga kalau beriklan di media cetak semacam ini.
Pembaca jurnalisme sastrawi tentulah kelompok yang tersegmentasi. Ini bisa kekurangan, tapi bisa juga peluang pemosisian. Mereka para intelektual, punya banyak waktu dan niat untuk membaca, penikmat sastra dan jurnalisme sekaligus, aktivis, dosen serta mahasiswa. Dengan kata lain, manajemen penerbitan jurnalisme sastrawi harus secara hati-hati mampu membaca pasar dan merekayasa perencanaan yang benar-benar matang.
Jalan tengahnya, ia mungkin bisa dipakai sebagai komplementer pada surat kabar konvensional, selingan, dan bukan gaya utama. Itu pun masih harus menyesuaikan diri dengan terbatasnya ketersediaan ruang.
Terlepas dari semua itu, jurnalisme sastrawi bisa menjadi sebuah metode penulisan tidak saja untuk surat kabar atau majalah, tapi juga untuk buku.




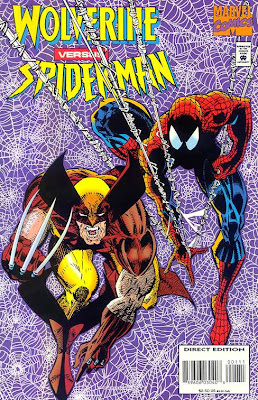
Comments